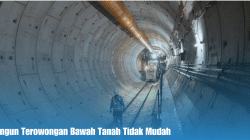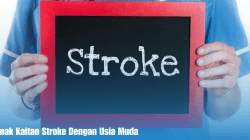Dmarket.web.id – Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah lama diwarnai ketegangan: defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok yang besar, persaingan teknologi dan rantai pasokan global yang semakin terfragmentasi, serta kekhawatiran Amerika atas praktik industri Tiongkok dan hak kekayaan intelektual.
Memasuki tahun 2025, administrasi AS yang baru mengambil langkah-langkah proteksionis yang lebih agresif dengan dalih memperbaiki posisi tawar AS, mempersempit defisit, dan menangani isu keamanan nasional, termasuk aliran obat sintetis (fentanyl) yang dikaitkan AS dengan Tiongkok.
Tiongkok, di sisi lain, memandang langkah AS sebagai tekanan yang tidak sah dan bersiap melakukan balasan. Konflik perdagangan ini kemudian berkembang cepat menjadi serangkaian tarif, pembatasan ekspor, dan eskalasi diplomatik.
Dinamika ini menjadi bagian dari kerangka persaingan besar antara dua kekuatan ekonomi global—dimana aspek ekonomi, teknologi, dan geopolitik saling berjalin.
Awal eskalasi: Februari – Maret 2025
Eskalasi resmi dimulai pada 4 Februari 2025, ketika AS memberlakukan tarif sebesar sekitar 10 % atas seluruh impor dari Tiongkok, sebagai bagian dari upaya menekan Tiongkok agar mengambil langkah lebih besar terhadap aliran fentanyl dan bahan bakunya.
Tindakan ini langsung memicu Tiongkok untuk melakukan balasan: memungut tarif 15 % terhadap impor AS seperti batu bara dan LNG, serta 10 % terhadap minyak mentah, mesin pertanian, dan beberapa kendaraan.
Pada 4 Maret 2025, AS kembali menaikkan tarif tambahan sekitar 10 %, sehingga total tarif terhadap barang-barang Tiongkok mencapai sekitar 20 %. Tiongkok merespons dengan meningkatkan tarif hingga 15 % untuk produk-produk pertanian AS seperti ayam, gandum, jagung, dan hingga 10 % untuk kedelai, daging babi, sapi, produk laut dan lainnya.
Pada fase ini, yang terjadi adalah awal dari siklus “aksi-reaksi”: AS menargetkan sektor impor dari Tiongkok dengan tarif, sementara Tiongkok segera memilih sektor sensitif AS—agrikultur, energi, dan mesin—untuk membalas. Dampaknya mulai terasa pada rantai pasokan, harga komoditas, dan iklim bisnis antar negara.
Titik puncak eskalasi: April 2025
Bulan April 2025 menandai titik puncak eskalasi tarif dan langkah-balik yang sangat tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS mengumumkan “Liberation Day tariffs”, yaitu paket tarif besar-besaran yang menaikkan beban impor dari Tiongkok secara sangat signifikan.
Paket ini menyatakan pengenaan tarif tambahan 34 % pada seluruh barang impor dari Tiongkok, di atas tarif sebelumnya.
Pada 4 April 2025, Tiongkok merespons dengan sangat cepat, mengumumkan tarif balasan 34 % terhadap seluruh barang impor AS serta menambah pembatasan ekspor bahan baku seperti rare earth dan meterial penting lainnya, bahkan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO).
Dalam hitungan hari, tarif yang dipungut kedua belah pihak melonjak: AS mencatat tarif penuh terhadap impor Tiongkok mencapai sekitar 145 % dalam beberapa kategori, sedangkan Tiongkok memberlakukan hingga sekitar 125 % pada barang-barang AS.
Eskalasi ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga mencakup pembatasan teknologi, larangan investasi, dan langkah-non-tarif lainnya: perusahaan AS diinvestigasi di Tiongkok, perusahaan Tiongkok dikenakan daftar hitam di AS, dan kedua negara mengkaitkan isu perdagangan dengan keamanan nasional dan teknologi tinggi.
Akibatnya, ketidakpastian menjadi sangat besar: eksportir dan importir di kedua negara harus mempertimbangkan risiko tarif yang berubah cepat, rantai pasokan terganggu, dan keputusan investasi tertunda.
Fase gencatan senjata sementara: Mei – Agustus 2025
Menyadari bahwa eskalasi terus-menerus akan merugikan kedua belah pihak, pada tanggal 12 Mei 2025, AS dan Tiongkok mengumumkan gencatan senjata sementara selama 90 hari.
Dalam kesepakatan tersebut, AS bersedia menurunkan tarif atas impor Tiongkok dari sekitar 145 % ke sekitar 30 %, sementara Tiongkok menurunkan tarif atas barang AS dari sekitar 125 % ke sekitar 10 %.
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan untuk meredam konflik sebelum meluas lebih jauh. Selama masa gencatan senjata, berlangsung pembicaraan dan negosiasi di Jenewa dan kemudian di London.
Pada 11–12 Agustus 2025, gencatan tersebut diperpanjang lagi selama 90 hari. AS menandatangani perintah eksekutif yang menunda kenaikan tarif besar berikutnya, sedangkan Tiongkok memberikan pembebasan terbatas bagi sebagian perusahaan AS yang terkena kontrol ekspor.
Namun, perlu ditegaskan bahwa meskipun tekanan mereda, banyak isu struktural utama (seperti hak kekayaan intelektual, subsidi industri Tiongkok, dan keamanan teknologi) belum terselesaikan.
Pada fase ini terjadi perubahan perilaku: banyak perusahaan mulai meninjau kembali rantai pasokan mereka—beberapa memindahkan sebagian produksi ke negara “China +1”, sementara yang lain mempertimbangkan diversifikasi ke Asia Tenggara. Risiko dan biaya logistik mulai meningkat.
Perkembangan lanjutan dan pengikatan teknologi: September – Oktober 2025
Memasuki musim gugur 2025, dinamika konflik bergeser dari tarif murni ke aspek teknologi, ekspor material kritis, dan blok-investasi. AS memperluas blacklist ekspor dan entitas yang dilarang melakukan kontak teknologi dengan perusahaan Tiongkok.
Tiongkok, pada gilirannya, meningkatkan kontrol ekspor bahan dasar seperti rare earths serta memberlakukan yurisdiksi ekstrateritorial dan “50% rule” terhadap ekspor yang memanfaatkan teknologi asing.
Kedua negara juga meluncurkan investigasi antimonopoli terhadap perusahaan teknologi dari pihak lainnya, misalnya Tiongkok menuding perusahaan AS melanggar aturan persaingan, sementara AS sedang menyelidiki bahwa Tiongkok tidak memenuhi komitmen sebelumnya dalam kesepakatan fase pertama.
Pada Oktober 2025, sumber-tertentu menunjukkan bahwa kedua pihak kembali menjajaki kerangka kerja perdagangan yang lebih luas untuk menunda atau menghindari pengenaan tarif 100 % yang pernah diancam.
Meski demikian, atmosfer masih panas: retorika keras muncul dari Tiongkok yang menyatakan siap “berjuang sampai akhir” dalam perang tarif maupun teknologi terhadap AS, dan AS tetap menggunakan alat proteksionis sebagai senjata dalam persaingan strategis.
Di lapangan, perusahaan multinasional mulai berposisikan ulang: produksi elektronik dan komponen kini harus mempertimbangkan risiko regulasi dan geopolitik, bukan sekadar biaya tenaga kerja.
Pasar komoditas seperti pertanian AS yang bergantung pada ekspor ke Tiongkok mengalami tekanan baru, sementara Tiongkok memperkuat hub pasokan di Asia dan Eropa sebagai mitigasi.
Dampak ekonomi, teknologi, dan rantai pasokan
Dampak perang dagang ini multifaset. Dari sisi ekonomi, tarif ekstrem menyebabkan peningkatan biaya impor, gangguan pada rantai pasokan global, serta tekanan pada kelompok industri yang sangat bergantung pada ekspor atau impor silang.
Penelitian menunjukkan bahwa tarif dan keterlambatan pengiriman akibat konflik memperbesar inventaris yang harus ditahan perusahaan, menurunkan output dan meningkatkan harga.
ari sisi teknologi, persaingan AS-Tiongkok mendorong fragmentasi rantai nilai global: perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga risiko geopolitik, kontrol ekspor, dan regulasi keamanan nasional.
Tiongkok meningkatkan posisi dalam rantai nilai global bagian hulu (intermediate goods), sedangkan AS dan perusahaan global semakin menjajaki strategi “China +1” untuk mengurangi ketergantungan langsung ke Tiongkok.
Secara struktural, konflik ini memperkuat tren de-globalisasi selektif dan regionalisasi rantai pasokan: wilayah Asia Tenggara, India, dan Meksiko mendapatkan perhatian sebagai alternatif produksi atau sourcing.
Selain itu, kebijakan proteksionis AS dan langkah balasan Tiongkok memperkokoh norma baru bahwa perdagangan besar kini sangat terkait dengan agenda geopolitik dan keamanan, bukan hanya ekonomi semata.
Dinamika politik dan diplomasi
Perang dagang ini juga memiliki dimensi politik domestik dan diplomatik yang kuat. Bagi AS, kebijakan tarif digunakan sebagai alat untuk memperkuat pesan “Amerika terlebih dahulu”, mendukung basis pemilih yang terdampak oleh globalisasi, terutama di sektor pertanian dan manufaktur.
Bagi Tiongkok, respons keras bertujuan mempertahankan kedaulatan ekonomi, menghindari tekanan eksternal terhadap model industrialisasi, dan menunjukkan bahwa negara akan menolak tekanan unilateral.
Secara diplomatik, negeri‐besar ini memperlihatkan bahwa ekonomi dan perdagangan tidak terpisah dari strategi geopolitik: konflik tarif menjadi bagian dari persaingan teknologi, pengaruh regional, dan perimbangan kekuatan global.
Meski terdapat upaya gencatan senjata sementara, path dependence (jalur sebelumnya) menunjukkan bahwa hubungan akan terus diuji oleh perubahan kepentingan nasional masing-masing.
Tantangan menuju penyelesaian
Walaupun terdapat kesepakatan sementara, banyak tantangan yang masih menghambat penyelesaian permanen: pertama, persoalan struktural seperti subsidi industri Tiongkok, akses pasar, perlindungan kekayaan intelektual, dan standar teknologi belum disepakati.
Kedua, konflik teknologi dan sekuritas (misalnya kontrol ekspor, investasi asing, dan rantai pasokan kritis) semakin kompleks dan menyentuh domain yang sulit dinegosiasikan.
Ketiga, tekanan domestik di kedua negara (kelompok industri, pemilih pertanian, tenaga kerja) mempersempit ruang gerak kompromi. Keempat, ruang lingkup global dan rantai pasokan yang terintegrasi menjadikan dampak konflik tidak hanya bilateral, melainkan multilateral—negara ketiga, perusahaan global, dan rantai nilai lintas negara turut terpengaruh.
Oleh karena itu, penyelesaian tidak hanya soal menurunkan tarif, tetapi juga soal membangun kerangka baru hubungan ekonomi yang mempertimbangkan keamanan, teknologi, dan nilai strategis.
Dalam konteks ini, negosiasi memerlukan bukan hanya perjanjian tarif, tetapi integrasi kebijakan industri, investasi, teknologi, dan hubungan geopolitik.
Prospek Masa Perang Dagang
Melihat situasi hingga akhir 2025, ada beberapa skenario yang mungkin terbuka. Skenario moderat adalah bahwa AS dan Tiongkok mencapai kesepakatan kerangka kerja yang lebih luas yang mencakup tarif, akses pasar, dan kontrol teknologi dalam perang dagang.
Namun, skenario pessimistik menunjukkan bahwa konflik bisa meluas: tarif bisa kembali naik, pembatasan teknologi bisa semakin ketat, dan persaingan rantai pasokan bisa mengarah ke pemisahan (decoupling) yang lebih tajam.
Terlebih lagi, perusahaan global akan terus menyesuaikan strategi mereka—memindahkan produksi, diversifikasi sumber, atau menyederhanakan rantai pasokan untuk mengakses pasar tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan drastis.
Bagi Tiongkok, memperkuat pasar domestik dan rantai nilai regional menjadi prioritas, sementara bagi AS, memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan strategis menjadi agenda utama.
Dalam jangka panjang, perang dagang ini dapat mempercepat tren fragmentasi ekonomi global, memperkuat regionalisme, dan meletakkan dasar bagi persaingan strategis yang lebih terbuka antara dua kekuatan besar.
Sistem perdagangan global mungkin perlu menyesuaikan mekanisme yang sebelumnya diasumsikan berbasis liberalisasi penuh—sekarang harus mengakomodasi realistis bahwa nasionalisme ekonomi dan keamanan menjadi faktor dominan.
Kesimpulan Perang Dagang Kedua Negara
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak awal 2025 menunjukkan bagaimana hubungan ekonomi besar dapat berubah cepat ketika dikaitkan dengan isu teknologi, keamanan, dan geopolitik.
Urutan kronologis dari tarif awal, eskalasi tajam, gencatan senjata sementara, hingga perpindahan ke domain teknologi dan rantai pasokan menggambarkan kompleksitas konflik modern.
Meskipun ada peluang untuk penyelesaian perang dagang, tantangan struktural yang mendalam dan konteks global yang berubah membuat jalan menuju kesepakatan permanen menjadi sulit dan panjang.
Konflik ini bukan hanya soal barang yang diperdagangkan hari ini, tetapi soal bagaimana dua bangsa terbesar dunia mendefinisikan posisi mereka dalam tatanan ekonomi dan teknologi global yang sedang berevolusi.